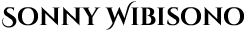Mengukur Kepantasan
Message of Monday – Senin, 4 Juli 2022
Mengukur Kepantasan
Oleh: Sonny Wibisono *
“Live one day at a time emphasizing ethics rather than rules.”
-- Wayne Dyer
Dalam beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan mengenai kehidupan mewah para petinggi satu lembaga filantropi. Isu itu menyeruak setelah satu majalah nasional melakukan investigasi jurnalistik dalam laporan utamanya yang terbit pada 2 Juni lalu. Sontak isu itu menjadi trending di media sosial. Laporan itu tak hanya membeberkan mengenai gaya hidup para petingginya yang dinilai mewah, tapi juga gaji para petingginya yang dinilai fantastis.
Para petinggi tersebut dikabarkan sempat menerima gaji Rp 250 juta per bulan. Walau kemudian dibantah tidak lagi sebesar itu. Dalam laporannya, disebutkan gaji pengurus berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 250 juta per bulan. Seorang ekonom menjelaskan, sebenarnya tak ada yang dilanggar serta tak ada yang menyalahi aturan terkait besaran gaji ini. Namun, ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa lembaga kemanusiaan juga harus menjunjung tinggi asas kepantasan dan memperhatikan rasa keadilan publik.
Pertanyaannya, seberapa pantas seorang menerima apa yang menjadi haknya? Dalam hal ini gaji untuk para petingginya. Sebenarnya, yang dapat mengukur kepantasan ialah diri kita sendiri. Memang sudah pasti bersifat subjektif. Bila bicara cukup, manusia tak akan pernah cukup. Ibarat pepatah, bila manusia diberi satu gunung emas, maka akan meminta satu gunung lagi.
Tapi, apakah pantas menerima gaji sebesar Rp 250 juta per bulan dengan segala fasilitas mewah yang didapat? Disini, hati nuranilah yang bicara. Walaupun seandainya kita dapat bertindak semaunya karena memiliki kewenangan, tetap hati nurani yang akan melihatnya secara jernih.
Patut diingat, uang yang diterima lembaga semacam filantropi tersebut merupakan uang titipan alias amanah dari para penyumbang. Lembaga filantropi bukanlah lembaga profit layaknya perusahaan yang mencari keuntungan.
Ah, saya jadi teringat satu kisah saat menjadi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid di kompleks perumahan yang saya tempati. Satu saat, para pengurus mengadakan rapat mengenai alokasi dana yang selama ini disumbangkan oleh jamaah. Uangnya memang tak banyak. Beberapa pengurus ada yang tidak sepakat dana disalurkan dalam kegiatan tertentu. Sebagian lain sepakat. Semua memiliki argumen dan dalil agama masing-masing.
Padahal, alokasi yang diperdebatkan itu pun bertujuan baik. Untuk kegiatan keagamaan juga. Hanya saja, dalam hal ini pengurus sangat berhati-hati dalam mengelola uang milik masyarakat. Mereka tak ingin ada kesalahan sedikitpun. Karena tanggungjawabnya tak hanya di dunia saja, tapi juga akhirat.
Menilik kasus di atas, pada akhirnya semua mengakar pada persoalan etika alias menakar kepantasan. Oleh karena itu, etika menjadi bagian yang penting bagi setiap individu, terutama mereka para petinggi dan karyawan yang bekerja di lembaga atau perusahaan. Untuk mengatur etika para petingginya termasuk karyawannya, pihak perusahaan menerbitkan kode etik atau biasa kita kenal sebagai code of conduct.
Hal yang sama juga berlaku di partai politik, lembaga pemerintahan, organisasi, asosiasi profesi, bahkan lembaga filantropi sekalipun. Dalam kasus lembaga filantropi tersebut, apakah kode etik sudah benar-benar dijalankan?
Disinilah pentingnya good governance atau tata kelola yang baik. Lembaga filantropi tersebut perlu melakukan audit untuk menjawab keraguan publik. Serta untuk mempertanggungjawabkan dana yang dikumpulkan dari para donatur atau jamaah.
Kasus yang mencuat di Indonesia ini hanyalah satu contoh saja. Bisa terjadi dimana saja dimana tata kelola tidak berjalan dengan baik. Tak peduli apakah itu suatu lembaga keagamaan atau bukan. Di Negeri Paman Sam belum lama ini juga pernah terjadi kasus yang mirip di negeri ini. Saat sang petinggi tersebut ditanya mengapa menggunakan pesawat jet setiap kali bepergian dalam berdakwah, jawabnya agar dapat melayani umat lebih baik.
Bicara etika, sejatinya bukan bicara soal ’boleh’ atau ’tidak boleh’. Karena soal ’boleh’ atau ’tidak boleh’, hal itu sudah diatur dalam peraturan. Bila Anda melanggar, Anda akan dikenakan sanksi. Tetapi bila bicara etika, maka kita bicara ’patut’ atau ’tidak patut’, ’pantas’ atau ’tidak pantas’. Dalam hal ini, etika lebih tinggi dari peraturan.
Saya sendiri sepakat, bahwa laporan investigasi jurnalistik tersebut bukanlah satu fakta hukum. Azas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Perlu dilakukan investigasi dan audit secara menyeluruh. Bila ada petinggi atau karyawan yang salah, tentu harus diberi sanksi.
Biar bagaimanapun, masyarakat tetap membutuhkan lembaga-lembaga semacam ini dengan catatan harus kredibel. Terlebih, indeks kedermawanan masyarakat Indonesia diyakini akan terjaga dan terus naik walaupun ada kasus yang terjadi pada satu filantropi di negeri ini.
Semoga ke depannya tingkat kesejahteraan masyarakat di tanah air makin meningkat, baik secara individu maupun korporasi, seiring gencarnya pembangunan yang terus digalakkan. Sehingga kepedulian kepada sesama turut meningkat. Dan, yang juga penting, semoga kasus ini menjadi yang terakhir menimpa filantropi di Tanah Air.
* Penulis buku ‘Message of Monday’, Elexmedia, 2009 dan Ref Grafika Publishing, 2012
Photo by Liza Summer: https://www.pexels.com/photo/crop-anonymous-person-showing-donation-box-6348119/
Mengukur Kepantasan
Oleh: Sonny Wibisono *
“Live one day at a time emphasizing ethics rather than rules.”
-- Wayne Dyer
Dalam beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan mengenai kehidupan mewah para petinggi satu lembaga filantropi. Isu itu menyeruak setelah satu majalah nasional melakukan investigasi jurnalistik dalam laporan utamanya yang terbit pada 2 Juni lalu. Sontak isu itu menjadi trending di media sosial. Laporan itu tak hanya membeberkan mengenai gaya hidup para petingginya yang dinilai mewah, tapi juga gaji para petingginya yang dinilai fantastis.
Para petinggi tersebut dikabarkan sempat menerima gaji Rp 250 juta per bulan. Walau kemudian dibantah tidak lagi sebesar itu. Dalam laporannya, disebutkan gaji pengurus berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 250 juta per bulan. Seorang ekonom menjelaskan, sebenarnya tak ada yang dilanggar serta tak ada yang menyalahi aturan terkait besaran gaji ini. Namun, ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa lembaga kemanusiaan juga harus menjunjung tinggi asas kepantasan dan memperhatikan rasa keadilan publik.
Pertanyaannya, seberapa pantas seorang menerima apa yang menjadi haknya? Dalam hal ini gaji untuk para petingginya. Sebenarnya, yang dapat mengukur kepantasan ialah diri kita sendiri. Memang sudah pasti bersifat subjektif. Bila bicara cukup, manusia tak akan pernah cukup. Ibarat pepatah, bila manusia diberi satu gunung emas, maka akan meminta satu gunung lagi.
Tapi, apakah pantas menerima gaji sebesar Rp 250 juta per bulan dengan segala fasilitas mewah yang didapat? Disini, hati nuranilah yang bicara. Walaupun seandainya kita dapat bertindak semaunya karena memiliki kewenangan, tetap hati nurani yang akan melihatnya secara jernih.
Patut diingat, uang yang diterima lembaga semacam filantropi tersebut merupakan uang titipan alias amanah dari para penyumbang. Lembaga filantropi bukanlah lembaga profit layaknya perusahaan yang mencari keuntungan.
Ah, saya jadi teringat satu kisah saat menjadi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid di kompleks perumahan yang saya tempati. Satu saat, para pengurus mengadakan rapat mengenai alokasi dana yang selama ini disumbangkan oleh jamaah. Uangnya memang tak banyak. Beberapa pengurus ada yang tidak sepakat dana disalurkan dalam kegiatan tertentu. Sebagian lain sepakat. Semua memiliki argumen dan dalil agama masing-masing.
Padahal, alokasi yang diperdebatkan itu pun bertujuan baik. Untuk kegiatan keagamaan juga. Hanya saja, dalam hal ini pengurus sangat berhati-hati dalam mengelola uang milik masyarakat. Mereka tak ingin ada kesalahan sedikitpun. Karena tanggungjawabnya tak hanya di dunia saja, tapi juga akhirat.
Menilik kasus di atas, pada akhirnya semua mengakar pada persoalan etika alias menakar kepantasan. Oleh karena itu, etika menjadi bagian yang penting bagi setiap individu, terutama mereka para petinggi dan karyawan yang bekerja di lembaga atau perusahaan. Untuk mengatur etika para petingginya termasuk karyawannya, pihak perusahaan menerbitkan kode etik atau biasa kita kenal sebagai code of conduct.
Hal yang sama juga berlaku di partai politik, lembaga pemerintahan, organisasi, asosiasi profesi, bahkan lembaga filantropi sekalipun. Dalam kasus lembaga filantropi tersebut, apakah kode etik sudah benar-benar dijalankan?
Disinilah pentingnya good governance atau tata kelola yang baik. Lembaga filantropi tersebut perlu melakukan audit untuk menjawab keraguan publik. Serta untuk mempertanggungjawabkan dana yang dikumpulkan dari para donatur atau jamaah.
Kasus yang mencuat di Indonesia ini hanyalah satu contoh saja. Bisa terjadi dimana saja dimana tata kelola tidak berjalan dengan baik. Tak peduli apakah itu suatu lembaga keagamaan atau bukan. Di Negeri Paman Sam belum lama ini juga pernah terjadi kasus yang mirip di negeri ini. Saat sang petinggi tersebut ditanya mengapa menggunakan pesawat jet setiap kali bepergian dalam berdakwah, jawabnya agar dapat melayani umat lebih baik.
Bicara etika, sejatinya bukan bicara soal ’boleh’ atau ’tidak boleh’. Karena soal ’boleh’ atau ’tidak boleh’, hal itu sudah diatur dalam peraturan. Bila Anda melanggar, Anda akan dikenakan sanksi. Tetapi bila bicara etika, maka kita bicara ’patut’ atau ’tidak patut’, ’pantas’ atau ’tidak pantas’. Dalam hal ini, etika lebih tinggi dari peraturan.
Saya sendiri sepakat, bahwa laporan investigasi jurnalistik tersebut bukanlah satu fakta hukum. Azas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Perlu dilakukan investigasi dan audit secara menyeluruh. Bila ada petinggi atau karyawan yang salah, tentu harus diberi sanksi.
Biar bagaimanapun, masyarakat tetap membutuhkan lembaga-lembaga semacam ini dengan catatan harus kredibel. Terlebih, indeks kedermawanan masyarakat Indonesia diyakini akan terjaga dan terus naik walaupun ada kasus yang terjadi pada satu filantropi di negeri ini.
Semoga ke depannya tingkat kesejahteraan masyarakat di tanah air makin meningkat, baik secara individu maupun korporasi, seiring gencarnya pembangunan yang terus digalakkan. Sehingga kepedulian kepada sesama turut meningkat. Dan, yang juga penting, semoga kasus ini menjadi yang terakhir menimpa filantropi di Tanah Air.
* Penulis buku ‘Message of Monday’, Elexmedia, 2009 dan Ref Grafika Publishing, 2012
Photo by Liza Summer: https://www.pexels.com/photo/crop-anonymous-person-showing-donation-box-6348119/
Latest Post
 Menyikapi No Buy Challenge 2025
Menyikapi No Buy Challenge 2025Sebelum berganti tahun 2025, di penghujung Desember 2024, kampanye ‘No Buy Challenge 2025’ menggema di berbagai media sosial. Bahkan tagar #NoBuyChallenge disematkan hampir lima puluh juta kali di TikTok dan merambat ke berbagai media sosial lainnya.
 Tergoda Isu Viral
Tergoda Isu ViralDalam beberapa hari terakhir ini di media sosial bersliweran isu mengenai kasus pernikahan satu keluarga yang viral. Isu ini bahkan oleh sebagian pihak dijadikan meme.
 Belanja Bijak, Belanja Cermat
Belanja Bijak, Belanja CermatBulan Desember identik dengan berbagai hal. Seperti peringatan Natal, musim dingin, atau perayaan tahun baru. Apa lagi? Tak hanya itu, Desember konon surganya bagi para konsumen untuk berbelanja dengan harga murah. Mengapa?
KOMENTAR