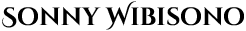BANJIR DAN KORUPSI
BANJIR DAN KORUPSI
Oleh: Sonny Wibisono *
Ibukota yang dulu pernah termasyhur sebagai Ratu dari Timur -Koningin van het Oosten,karena arsitek dan bangunannya yang mirip dengan Eropa, akan terlihat seperti kolam raksasa bila dilihat dari atas ketika banjir menerjang Jakarta 2 Februari lalu. Dalam sejarahnya, Jakarta sendiri pernah mengalami kegagalan dalam mengelola lingkungan hidupnya. Hal itulah yang menyebabkan dibentuknya Batavia baru (Niew Batavia) di Weltevreden (sekitar Gambir saat ini). Simon Stevin, arsitek pertama Batavia lama (oud Batavia)di tahun 1618, tentu tak pernah berpikir, bahwa ratusan tahun kemudian hasil karyanya, pada hari naas tersebut lumpuh akibat hujan yang terus-menerus mengguyur Jakarta selama beberapa jam. Banjir hebat yang melanda Jakarta selama beberapa hari tersebut, merupakan ulangan dari apa yang terjadi pada tahun 1621, 1654, 1918, 1942, 1976, 1996, dan terakhir di tahun 2002. Curah hujan yang cukup tinggi, dataran yang hampir setengahnya lebih rendah dari lautan, serta berjejalnya 13 sungai yang mengelilingi kota Jakarta, membuat kota ini sulit menghindar dari serbuan bah. Keadaan dan kondisi tersebut bukannya tidak diketahui oleh para pejabat yang berwenang dalam mengurus Kota Jakarta. Bahkan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres (8/2/200) mengatakan sebenarnya sudah diketahui cara mengatasi banjir, karena konsepnya bukan sesuatu yang baru. Nah, mengapa kita tidak mengambil pelajaran dari musibah di tahun 2002 lalu? Bahkan banjir yang baru saja melanda Jakarta justeru semakin dahsyat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebanyak 55 korban meninggal dunia, warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga Rabu (7/2) lalu, serta tak kurang dari Rp 4,1 triliun kerugian ekonomi sampai triliunan rupiah kerugian material yang ditimbulkan akibat bencana tersebut.
Pertanyannya, mengapa banjir yang melanda Jakarta makin bertambah dahsyat saja? Berdasarkan data pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) DKI Jakarta 2010, luas lahan terbangun di Jakarta Barat pada tahun 1993 mencapai 55,45 persen dan meningkat menjadi 76,93 persen pada tahun 2003. Kenaikan luas lahan terbangun itu semakin cepat seiring dengan laju membaiknya ekonomi. Pada tahun 2006, lebih dari 30 pertokoan, apartemen, dan perkantoran skala besar dibangun di seluruh Jakarta. Pada periode 2007 - 2008, sekitar 80 pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran baru akan dibangun di Jakarta. Pembangunan gedung-gedung tersebut dan juga bertambahnya pemukiman, justeru ditenggarai menyebabkan hilang dan rusaknya situ-situ, yang merupakan daerah resapan air, yang ada di wilayah Jabotabek. Keadaan ini diperparah dengan menjamurnya pembangunan vila-vila dan perumahan di kawasan Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur) dan sekitarnya yang menyebabkan daerah resapan air di daerah tersebut semakin berkurang. Kerusakan yang terjadi pada situ ditandai dengan adanya pendangkalan situ, pengurukan situ, dan alih fungsi situ. Hampir sebagian kerusakan itu terjadi karena terdesak oleh kawasan permukiman. Sekitar 80 persen situ yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diketahui mengalami kerusakan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, ada 205 situ di Jabodetabek yang saat ini mengalami kerusakan. Dari jumlah itu, 115 diantaranya dalam kondisi kritis dan sisanya rusak sedang.
Banjir yang melanda Jakarta sebenarnya dapat diminimalisir kerugiannya bila para pejabat berwenang tak seenaknya menorehkan paraf dan tanda tangannya dalam mengeluarkan perizinan bagi pembangunan gedung dan perumahan. Penyebab utama terjadinya banjir hebat di Jakarta merupakan akumulasi dari praktik-praktik korupsi yang berlangsung selama ini. Lemahnya koordinasi dalam perencanaan tata ruang, praktik korupsi dalam “jual beli” izin peruntukan lahan, serta lemahnya law enforcementbagi pelanggar izin karena adanya praktik pat-gulipatantara pejabat pemberi izin, aparat hukum, dan pemilik modal merupakan faktor-faktor yang tak bisa diabaikan sebagai biang keladi banjir hebat yang melanda Jakarta. Begitu mudahnya izin diberikan dapat terlihat dari variabel semakin sedikitnya ruang terbuka hijau (RTH) sebagai kawasan tangkapan dan resapan air, serta semakin banyaknya kawasan parkir air yang hilang berupa situ, danau, dan rawa-rawa. Dalam Master Plan DKI 1965-1985, RTH masih 27,6%, kemudian proyeksi versi pemerintah pada tahun 1985-2005 RUTR DKI masih menyisakan RTH 26,1%. Tahun 2000-2010, menurut RUTR, DKI hanya memproyeksikan RTH 13 persen. Target RTH DKI pada tahun 2010 itu adalah 9.544 hektar (ha). Padahal, realisasi tahun 2003 hanya 7.390 ha. Hal ini memperlihatkan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap RTH. Dari data tersebut terlihat bahwa hal ini terjadi pada tahun 1997 dan mengalami peningkatan tajam di tahun 1999-2001. Contoh alih fungsi yang nampak kasat mata, seperti pembangunan apartemen di wilayah selatan Jakarta serta hutan kota di Cibubur yang dijual untuk dikonversi menjadi pembangunan kawasan komersial. Nasi memang sudah menjadi bubur. Sekarang bagaimana mengatasi bencana tersebut agar tak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sendiri berencana mengimplementasikan pembenahan dan penanggulangan banjir secara struktural dan menyeluruh dari hulu dan hilir secara serius dan terpadu dalam jangka menengah dengan anggaran yang cukup terutama di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Langkah ini tentu harus kita dukung sepenuhnya. Hal ini tentu saja dibarengi dengan law enforcementyang harus berjalan tanpa pandang bulu dalam menertibkan dan melaksanakan tata ruang Kota Jakarta sebagaimana mestinya. Sedangkan 3 Rancangan Undang–Undang (RUU) yaitu RUU Pemerintahan Ibukota, RUU Bencana Alam, dan RUU Tata Ruang, sebagai landasan hukum untuk mengantisipasi bahaya banjir di masa mendatang harus segera diselesaikan oleh DPR untuk segera diundangkan.
* Sonny Wibisono, penulis, tinggal di Jakarta
Pernah dimuat di Koran Tempo - Sabtu, 17 Februari 2007
Oleh: Sonny Wibisono *
Ibukota yang dulu pernah termasyhur sebagai Ratu dari Timur -Koningin van het Oosten,karena arsitek dan bangunannya yang mirip dengan Eropa, akan terlihat seperti kolam raksasa bila dilihat dari atas ketika banjir menerjang Jakarta 2 Februari lalu. Dalam sejarahnya, Jakarta sendiri pernah mengalami kegagalan dalam mengelola lingkungan hidupnya. Hal itulah yang menyebabkan dibentuknya Batavia baru (Niew Batavia) di Weltevreden (sekitar Gambir saat ini). Simon Stevin, arsitek pertama Batavia lama (oud Batavia)di tahun 1618, tentu tak pernah berpikir, bahwa ratusan tahun kemudian hasil karyanya, pada hari naas tersebut lumpuh akibat hujan yang terus-menerus mengguyur Jakarta selama beberapa jam. Banjir hebat yang melanda Jakarta selama beberapa hari tersebut, merupakan ulangan dari apa yang terjadi pada tahun 1621, 1654, 1918, 1942, 1976, 1996, dan terakhir di tahun 2002. Curah hujan yang cukup tinggi, dataran yang hampir setengahnya lebih rendah dari lautan, serta berjejalnya 13 sungai yang mengelilingi kota Jakarta, membuat kota ini sulit menghindar dari serbuan bah. Keadaan dan kondisi tersebut bukannya tidak diketahui oleh para pejabat yang berwenang dalam mengurus Kota Jakarta. Bahkan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres (8/2/200) mengatakan sebenarnya sudah diketahui cara mengatasi banjir, karena konsepnya bukan sesuatu yang baru. Nah, mengapa kita tidak mengambil pelajaran dari musibah di tahun 2002 lalu? Bahkan banjir yang baru saja melanda Jakarta justeru semakin dahsyat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebanyak 55 korban meninggal dunia, warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga Rabu (7/2) lalu, serta tak kurang dari Rp 4,1 triliun kerugian ekonomi sampai triliunan rupiah kerugian material yang ditimbulkan akibat bencana tersebut.
Pertanyannya, mengapa banjir yang melanda Jakarta makin bertambah dahsyat saja? Berdasarkan data pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) DKI Jakarta 2010, luas lahan terbangun di Jakarta Barat pada tahun 1993 mencapai 55,45 persen dan meningkat menjadi 76,93 persen pada tahun 2003. Kenaikan luas lahan terbangun itu semakin cepat seiring dengan laju membaiknya ekonomi. Pada tahun 2006, lebih dari 30 pertokoan, apartemen, dan perkantoran skala besar dibangun di seluruh Jakarta. Pada periode 2007 - 2008, sekitar 80 pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran baru akan dibangun di Jakarta. Pembangunan gedung-gedung tersebut dan juga bertambahnya pemukiman, justeru ditenggarai menyebabkan hilang dan rusaknya situ-situ, yang merupakan daerah resapan air, yang ada di wilayah Jabotabek. Keadaan ini diperparah dengan menjamurnya pembangunan vila-vila dan perumahan di kawasan Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur) dan sekitarnya yang menyebabkan daerah resapan air di daerah tersebut semakin berkurang. Kerusakan yang terjadi pada situ ditandai dengan adanya pendangkalan situ, pengurukan situ, dan alih fungsi situ. Hampir sebagian kerusakan itu terjadi karena terdesak oleh kawasan permukiman. Sekitar 80 persen situ yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diketahui mengalami kerusakan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, ada 205 situ di Jabodetabek yang saat ini mengalami kerusakan. Dari jumlah itu, 115 diantaranya dalam kondisi kritis dan sisanya rusak sedang.
Banjir yang melanda Jakarta sebenarnya dapat diminimalisir kerugiannya bila para pejabat berwenang tak seenaknya menorehkan paraf dan tanda tangannya dalam mengeluarkan perizinan bagi pembangunan gedung dan perumahan. Penyebab utama terjadinya banjir hebat di Jakarta merupakan akumulasi dari praktik-praktik korupsi yang berlangsung selama ini. Lemahnya koordinasi dalam perencanaan tata ruang, praktik korupsi dalam “jual beli” izin peruntukan lahan, serta lemahnya law enforcementbagi pelanggar izin karena adanya praktik pat-gulipatantara pejabat pemberi izin, aparat hukum, dan pemilik modal merupakan faktor-faktor yang tak bisa diabaikan sebagai biang keladi banjir hebat yang melanda Jakarta. Begitu mudahnya izin diberikan dapat terlihat dari variabel semakin sedikitnya ruang terbuka hijau (RTH) sebagai kawasan tangkapan dan resapan air, serta semakin banyaknya kawasan parkir air yang hilang berupa situ, danau, dan rawa-rawa. Dalam Master Plan DKI 1965-1985, RTH masih 27,6%, kemudian proyeksi versi pemerintah pada tahun 1985-2005 RUTR DKI masih menyisakan RTH 26,1%. Tahun 2000-2010, menurut RUTR, DKI hanya memproyeksikan RTH 13 persen. Target RTH DKI pada tahun 2010 itu adalah 9.544 hektar (ha). Padahal, realisasi tahun 2003 hanya 7.390 ha. Hal ini memperlihatkan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap RTH. Dari data tersebut terlihat bahwa hal ini terjadi pada tahun 1997 dan mengalami peningkatan tajam di tahun 1999-2001. Contoh alih fungsi yang nampak kasat mata, seperti pembangunan apartemen di wilayah selatan Jakarta serta hutan kota di Cibubur yang dijual untuk dikonversi menjadi pembangunan kawasan komersial. Nasi memang sudah menjadi bubur. Sekarang bagaimana mengatasi bencana tersebut agar tak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sendiri berencana mengimplementasikan pembenahan dan penanggulangan banjir secara struktural dan menyeluruh dari hulu dan hilir secara serius dan terpadu dalam jangka menengah dengan anggaran yang cukup terutama di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Langkah ini tentu harus kita dukung sepenuhnya. Hal ini tentu saja dibarengi dengan law enforcementyang harus berjalan tanpa pandang bulu dalam menertibkan dan melaksanakan tata ruang Kota Jakarta sebagaimana mestinya. Sedangkan 3 Rancangan Undang–Undang (RUU) yaitu RUU Pemerintahan Ibukota, RUU Bencana Alam, dan RUU Tata Ruang, sebagai landasan hukum untuk mengantisipasi bahaya banjir di masa mendatang harus segera diselesaikan oleh DPR untuk segera diundangkan.
* Sonny Wibisono, penulis, tinggal di Jakarta
Pernah dimuat di Koran Tempo - Sabtu, 17 Februari 2007
KOMENTAR